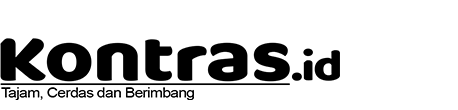Oleh : Zulkarnain Musada
Kontras.id (Opini) – “Jangan berdebat dengan orang idiot, mereka akan menyeretmu turun kedalam tingkat mereka dan kemudian mengalahkanmu dengan pengalamannya“. Mark Twain, Novelis Amerika (1835-1910).
Watak subjektivisme mendominasi serentak memerangi jalan konstan dalam ruang dialektis demokrasi dan ruang publik dengan wajah penuh intrik. Menjamurnya subjektivisme terendus ketika berbagai pihak dengan segala cara berusaha melabelkan ke-aku-an dalam ruang publik.
Dominasi subjektif yang kental ini menampakan diri secara benderang. Bukan saja dalam media sosial (Medsos) sebagai jejaring mainstream, tetapi juga secara praksis. Seperti misalnya menjadi pihak oposan dalam ruang demokrasi yang banyak ditunggangi kepentingan parsial.
Terlepas dari intensi menciptakan “kewarasan” publik, watak subjektivistik ini pun acap kali secara tak kasat mata menunggangi argumentasi substansial yang sesungguhnya melemahkan bobot rasional.
Di era pasca-kebenaran ini, watak itu justru diperlihatkan secara jelas di mana orang bertindak hanya atas dasar sentimen dan emosi yang diproduksi lewat isu-isu sosial, prestise, dan kekuasaan yang memancing agresivitas dengan sangat kuat. Peluang subjektivisme ini justru mencuat dalam media sosial dimana realitas konkret telah digusur dan rentetan fakta bisa sedemikian ideal diciptakan demi memenuhi hasrat kepentingan.
Maka, kita perlu memeriksa detail-detail yang jelas antara kehadiran media sosial, dan terjebaknya masyarakat publik pada subjektivisme yang bisa melumpuhkan cita rasa keberagaman seperti isu sosial-politik, ekonomi, hoax, hate speech, dan lain-lain.
Dalam bukunya “Homo Deus, Masa Depan Umat Manusia”, Yuval Noah Harari (2019) menemukan suatu penyakit akut yang sedang diderita manusia modern. Ia sebut sebagai FOMO (Fear Of Missing Out) atau penyakit “takut ketinggalan”.
Manusia berhadapan dengan jalan “acak” yang mengaburkan otentisitas diri dan terjebak dalam kesibukan individual. Ketakutan muncul karena sensasi subjektivistik dirasa makin jauh untuk diraih kendati manusia tetap berjuang dalam segala upaya dan kondisi demi keberadaan “ada”-nya. Ia muncul pertama kali tatkala orang dengan sangat ambisius melerai diri ataupun koloninya dari klaim-klaim kelompok lain.
Dengan cara demikian, ruang bagi terbukanya diskursus direpresi atau bahkan dipenggal. Pada saat yang sama, kelompok semacam ini terjebak pada kepedean serentak memenggal apa yang oleh Lefort sebagai-suatu ruang hampa (empty place) bagi tumbuhnya respons konstruktif pihak yang “berbeda”. Fenomena semacam ini perlu dibaca dalam konteks media sosial (virtual) yang menguasai peradaban dewasa ini.
Kewarasan bersuara kosong pada subjektivisme media sosial sesungguhnya berangkat dari tendensi keterpesonaan pada keluasan jaringan (internet) yang membuat manusia membayangkan internet sebagai sebuah kombinasi (Supeli, 2010). Kombinasi yang dimaksud ialah bahwa keluasan jaringan itu menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia; jejaring sebagai perpustakaan, pusat belanja, koran, ruang hobi, dan lain-lain.
Realitas menjadi ruang amat kecil yang mudah dijangkau. Keterpesonaan terhadap media sosial ini yang memungkinkan mereka tidak hanya menonton suatu dunia yang ditampilkan, tetapi memungkinkan orang juga untuk masuk, menghuni, dan tinggal di dalamnya (Supeli, Ibid).
Keterpesonaan itu makin akut terbaca pada realitas media sosial (virtual) di mana orang makin terpacu untuk masuk dan tinggal dengan multi-cara dan bertendensi mengabaikan kedalaman berpikir. Indikasi yang paling nyata ditemukan adalah membanjirnya postingan-postingan yang bermuatan politisasi aktivitas, kebenaran tunggal, intimidasi, emosi, dan tendensi temperamental, serta lainnya.
Keterjebakan media sosial ialah ketika mereka dikerangkeng dan tidak mampu menentukan batas bagi dirinya sendiri. Internet-media sosial dengan demikian menjadi sebuah kekuatan deterministik yang terbebas dari kontrol kecuali oleh dirinya sendiri dan bebas mengontrol masyarakatnya (Gibson, dikutip dalam Supelli 2010).
Dalam media sosial, semua orang terlibat secara reaktif. Ruang ini dikatakan sebagai ruang “ketelanjangan” yang pregiven (terberi) karena kebebasan individu termanifestasi secara merdeka tanpa introspeksi yang mumpuni.
Konsekuensi logisnya ialah kebebasan itu menjadi sebuah tanggung jawab personal dengan segala ke-aku-an yang melekat dalam diri masing-masing pribadi. Ruang yang demikian bebas ini menimbulkan suatu kepercayaan akan independensi diri sebagai penentu nilai etis dan kebaikan.
Lanskap publik justru menyediakan semacam “kaplingan” lahan yang lapang untuk direduksi secara semena-mena. Yang patut diterima di sini adalah subjektivitas hadir dengan wajah ganda untuk eksis dan ambisius menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya sudah membawa dalam dirinya suatu klaim kebenaran.
Pada titik ini, menurut hemat penulis, kebenaran yang dipersepsi oleh orang lain besar kemungkinan dianggap sebagai pemantik api perpecahan, penyulut kebencian serta kepercayaan diri (kebenaran) yang tunggal. Etika dan norma yang dijunjung bersama adalah urusan belakang. Dengan demikian, subjektivisme pun tumbuh dengan sangat kondusif. Watak ini tak terpisah dari kepedean (PeDe) yang pada akhirnya menggiring orang untuk eksis dengan segala cara yang tentu bertendensi lepas dari kerangka etis.
Percaya diri (PeDe) bisa dimengerti sebagai “hal atau keadaan sikap memiliki keyakinan atas diri sendiri sehingga dalam tindakannya tidak terlalu cemas, merasa bebas melakukan hal-hal yang sesuai dengan keinginan secara berlebihan”. PeDe yang minus nalar tampak dalam setiap postingan yang membanjir dalam media sosial.
Kita mendapati upaya mengondisikan ruang yang bebas itu dengan klaim-klaim personal yang syarat muatan intrik. Muatan intrik itu menyusup tatkala nalar dikolapskan berhadapan dengan hasrat keakuan yang terlampau menggebu.
Penyebab utama PeDe ialah hasrat untuk tampil seideal mungkin dengan segala cara yang dianggap cukup untuk memikat atensi publik. Hasrat itu pada dasarnya sudah inheren dalam setiap manusia dan menjadi sesuatu yang melekat serentak dapat memengaruhi dimensi eksistensial manusia.
Akan tetapi, hasrat itu berbalik buas tatkala timbulnya obsesi untuk “menaklukan” yang lain dan membiarkan diri terjerumus dalam keabsenan nalar. Di sini, kepedean berbalik menjadi suatu hasrat yang di dalamnya terkontaminasi keinginan untuk “memangsa” orang lain dan tentu upaya memproklamirkan diri sebagai pahlawan.
Mengentalnya PeDe terlihat ketika persaingan eksis yang kian hari kian ramai pada ruang publik dengan saling unjuk diri dan akhirnya terjebak pada usaha saling mengobjektivasi. Pengaruh-pengaruh subjektivisme dan kepedean ini pun menimbulkan suatu ekstremisme semu ataupun, menurut hemat penulis, menjadi basis pergerakan “pragmatisme pola pikir (PARKIR)”.
Dalam media sosial, setiap orang mampu menjadi siapa saja yang mampu mengobjektivasi yang “lain” dalam gerak pemikirannya sendiri. Kepedean, dengan demikian menjadi basis bertumbuhnya kaum pragmatisme pola pikir (PARKIR) karena media mainstream adalah sasaran para PARKIR memanifestasikan jalan pemikirannya.
Cara kerja kaum PARKIR menyusup pertama kali pada media mainstream. Karena di sanalah tercipta peluang untuk mengakomodasi ruang, memperkeruh keadaban publik, dan bisa juga mencaplok ruang dialektis.
“Empty Place” diperkenalkan oleh Lefort yang menempatkan pemikirannya dalam konteks demokrasi. Empty Place, secara harfiah, berarti ruang kosong. Suatu situasi di mana orang dimungkinkan masuk dan menimba sesuatu dari suatu lanskap yang kosong.
Di sini, Lefort hendak menunjukan suatu fakta sekaligus keprihatinannya akan raibnya ruang dialektis (yang menjadi ciri khas demokrasi). Ruang itu tak lagi tercipta. Karena mencuatnya berbagai klaim-klaim kebenaran parsial yang lebih menonjolkan eksklusivisme berpikir.
Jika Lefort pada zamannya melihat keprihatinan demokrasi dalam konteks eklusivisme berpikir, maka situasi itu tak ubahnya dengan konteks sekarang. Yakni, yang lebih menonjolkan realitas virtual ketimbang realitas konkret dengan segala macam “kesibukan”-nya.
Ada dua indikasi yang dikemukakan di sini. Pertama, adanya penetrasi media sosial yang menimbulkan adiksi (kecanduan). Media sosial bekerja dalam sistem algoritma yang membaca kebutuhan dan keinginan masyarakatnya. Algoritma bekerja dengan suatu strategi di mana agar ruang Medsos itu tetap dilintasi.
Masyarakat media sosial mudah terjebak ketika kebutuhan-kebutuhannya terasa dipenuhi secara kombinatif. Justru dalam keterjebakan itu, ia makin dipacu untuk terlibat dan membuka ruang. Walhasil, orang merasa tetap terdesak untuk eksis di media sosial. Walaupun tidak ada hal substansial yang cukup urgen.
Dengan demikian, ruang bagi terbukanya hoax makin lebar. Hoax tercipta karena ada keterdesakan untuk eksis. Walaupun tidak ditunjang dengan pertimbangan rasional yang mumpuni.
Hal ini pun berlaku bagi para korban hoax. Di sana ada eksklusivisme berpikir dengan klaim-klaim kebenaran yang palsu dan manipulatif. Karena kesibukan ini, “empty place” itu raib, hilang, dan tergerus.
Kedua, menguatnya rasionalitas instrumental. Rasionalitas instrumental berarti cara berpikir dengan menggunakan strategi-strategi untuk memperalat orang lain.
Rasionalitas macam ini merupakan dampak langsung dari penetrasi media sosial. Rasionalitas ini menampakkan semacam wajah barbar manusia kepada sesamanya dengan memproduksi sebanyak mungkin komunikasi non-etis, provokasi, dan hate speech. Alhasil, realitas media sosial menjadi sebuah ruang dimana pertempuran sentimental, sarat kepentingan kelompok, dan sebagainya terjadi tanpa sedikit pun mengupayakan dialog-dialog yang menyejukkan.
Lawan dari rasionalitas instrumental adalah apa yang oleh Jurgen Habermas sebuat sebagai Rasionalitas Komunikatif. Di sini ruang publik seharusnya menjadi suatu ruang komunikasi secara rasional tanpa sentimen. Rasionalitas Komunikatif mengupayakan adanya keterbukaan untuk menerima “yang lain” dalam keberagaman perspektif.
Akhirnya, kita tak mampu mengelak bahwa media sosial pun memiliki sumbangan positif demi kemajuan peradaban. Akan tetapi, perlu diingat bahwa upaya melabelkan ke-aku-an di dalam ruang itu pun sering terjadi. Ketika orang masuk dalam media sosial, dalam kesibukan yang tiada henti, orang justru memproduksi kebohongan, kebencian atau justru perpecahan di tengah cita rasa keberagaman yang majemuk ini.
Di sini perlu suatu awasan dan terlebih upaya pribadi untuk tidak terjebak dalam tindakan demikian. Yang perlu diupayakan ialah keterbukaan, suatu pengakuan akan yang lain, yang berbeda yang terjalin dalam suatu rasionalitas komunikatif.
Dengan pengakuan yang lain, apa pun perkembangan peradaban, termasuk media sosial pun, tidak menggerus manusia kepada sikap saling melenyapkan dan tindakan atas dasar sentimen semata.
Mari kita menjadi masyarakat media sosial yang bijak dengan menjunjung tinggi alteritas, semangat pluralistik, tanpa melabelkan ke-aku-an dalam kehidupan dan media sosial khususnya. “Empty place” ruang kosong harus selalu diupayakan. Karena di dalamnya penerimaan akan yang lain itu dapat dimungkinkan.(**).